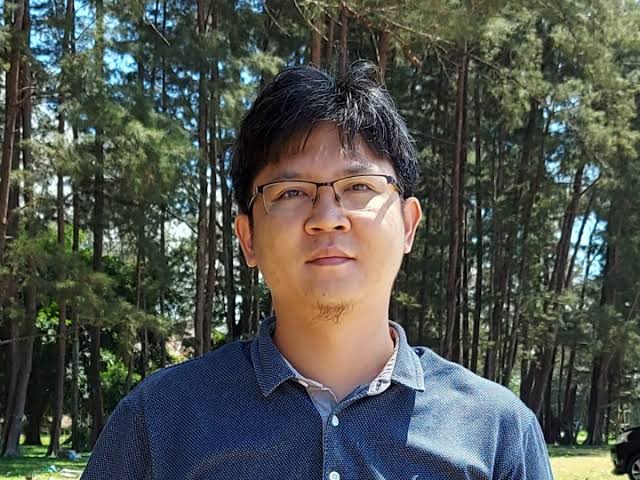Samarinda, Sekala.id – Isu politik uang terus menjadi sorotan di setiap pemilu. Dosen Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menjelaskan bahwa politik uang pada awalnya dipahami secara luas dan abstrak, tanpa batasan yang jelas. Praktik ini mencakup berbagai transaksi, termasuk suap dan penggelapan.
“Seiring waktu, makna politik uang semakin dipersempit,” ungkap Herdiansyah.
Ia mengutip Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, yang menyatakan bahwa politik uang kini merujuk pada distribusi uang atau barang dari kandidat kepada pemilih selama pemilu. Fenomena ini sudah diatur dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 187A, yang menegaskan ancaman pidana bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima.
Meski aturan sudah ada, kejahatan politik uang terus marak, bahkan meningkat dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Data dari Bawaslu menunjukkan, pada Pilkada 2020, terdapat 262 kasus dugaan politik uang yang sudah dalam tahap penyelidikan, dengan enam putusan bersalah.
“Bukti-bukti ini menegaskan bahwa aturan tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan efektif,” tegas Herdiansyah.
Survei LSI menunjukkan bahwa politik uang masih terjadi pada Pilkada 2020. Sebanyak 21,9 persen responden di tingkat provinsi dan 22,7 persen di tingkat kabupaten/kota mengaku pernah ditawari uang atau barang untuk memilih kandidat tertentu.
Herdiansyah menyoroti bahwa faktor-faktor seperti kondisi sosial-ekonomi dan rendahnya kesadaran politik menjadi penyebab suburnya politik uang. Semakin pragmatis masyarakat, semakin mudah mereka menerima tawaran uang demi memenuhi kebutuhan hidup.
Pada akhirnya, pemilih yang miskin dan kurang berpendidikan lebih rentan terhadap praktik jual-beli suara, sementara kandidat yang kurang populer atau berpengaruh menggunakan uang sebagai jalan pintas untuk meraih kemenangan.
“Politik uang adalah cerminan dari krisis kader di partai politik, di mana kandidat lebih dipilih karena kekuatan finansial daripada kapasitas dan integritas mereka,” tutupnya. (Kal/El/Sekala)